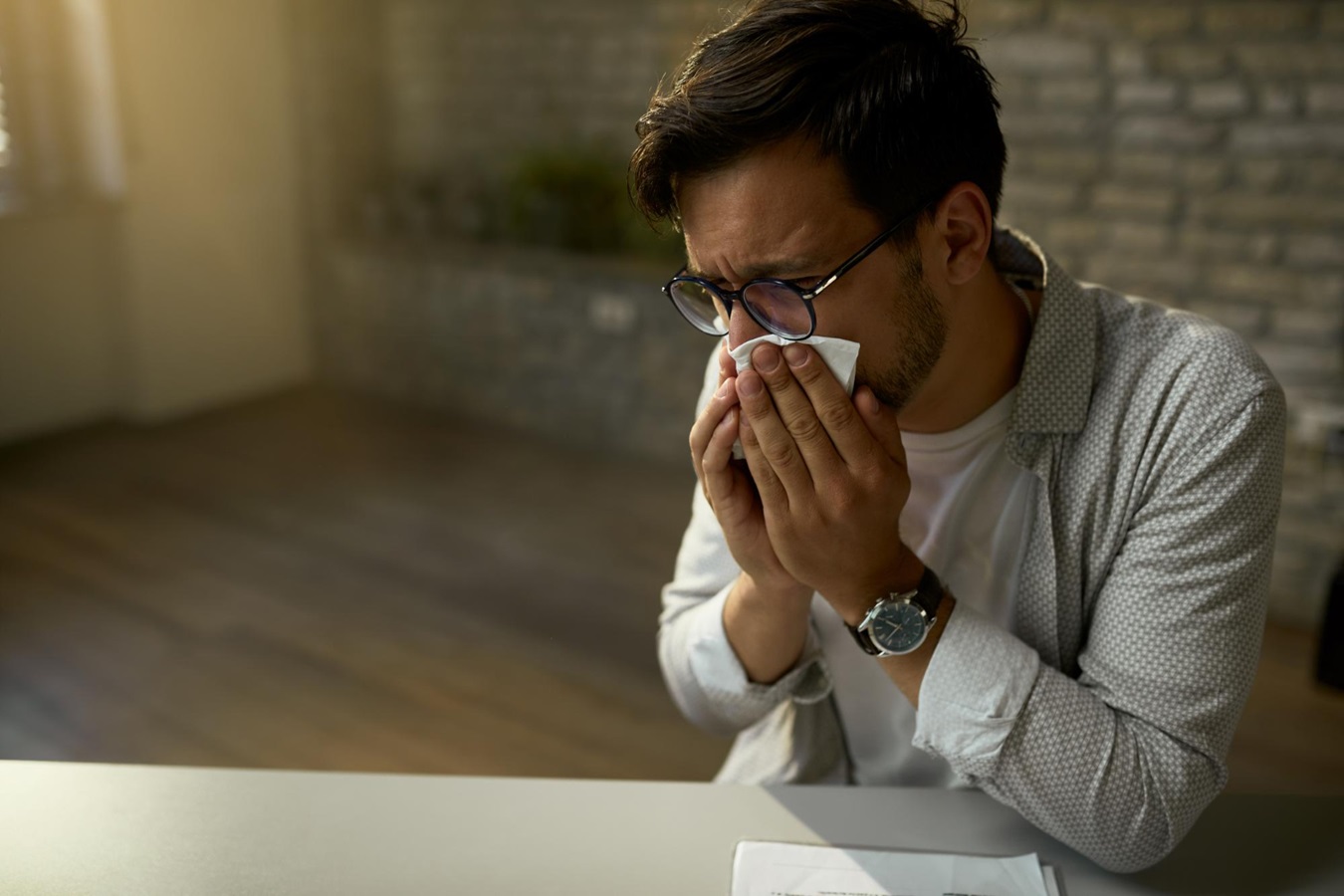Oleh: Tulus Warsito
23 Mei 2025 10.15 WIB – Umum
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pengantar: Pada 17 Mei 2025, telah berlangsung Panel Forum yang bertajuk “Pertemuan Dua Tradisi”. Diskusi Panel ini diselenggarakan di Ruang BA 201 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM (pukul 09.00 – 12.00 WIB). Diskusi menghadirkan narasumber Prof. Dr. M. Baiquni, M.A.; Prof. Subejo, S.P., M.Sc., Ph.D; Prof. Dr. Tulus Warsito, M.Si.; Prof. Drs. M. Mukhtasar Syamsuddin, M.Hum., Ph.D of Arts.; Pinurba Parama Pratiyudha, S.Sos., M.A., dan perwakilan desa: Masduki Rahmad, S.I.P., Malik Khairul Anam, dan Sayudi Anom Jayadi. Berikut ini adalah makalah dari Prof. Tulus Warsito.
Mencermati istilah dialog antara“tradisi pemikiran akademi” dan “tradisi pemikiran desa” perlu penegasan yang lebih sederhana bahwa yang dimaksud dengan keduanya adalah mengenai “kebiasaan di kampus” dan “kebiasaan di desa”, atau sederhananya adalah dialog antara “kampus” dan “desa”. Oleh karena itu menjadi penting untuk lebih dulu memahami apa itu kampus apa itu desa.
Kampus adalah tempat orang belajar tentang apa saja. Dalam jenisnya yang paling lengkap disebut universitas, atau university, yang artinya semesta atau ke-semesta-an. Sehingga kampus idealnya adalah tempat orang mempelajari alam semesta, meliputi ilmu-ilmu alam, sosial-humaniora dan seni, serta teknologi. Dalam bentuknya yang agak sederhana disebut institut, dan (yang lebih sederhana lagi) akademi. Ketiga-tiganya, baik yang lengkap maupun yang sederhana, pengertian intinya mengenai kampus adalah tempat orang mencari dan mengkonstruksi jawaban atas masalah (pertanyaan) tentang kehidupan manusia.
Sedangkan desa, dalam perbedaannya dengan kota, adalah wilayah yang jauh dari kota, memiliki kepadatan penduduk yang rendah (dibandingkan dengan kota), ekonominya berbasis pertanian, perkebunan, atau peternakan sebagai sumber utama pendapatan, lingkungan yang lebih alami. Dalam istilah ilmu sosial dirinci menjadi urban (perkotaan), sub-urban (pinggiran kota atau desa yang dekat dengan kota) dan rural (pedesaan). Dalam kasus Indonesia, desa tidak saja harus dibedakan “tradisi”-nya dalam konteks sub-urban dan rural, melainkan juga posisi geografi dalam konstelasi sosial-ekonomi-politik Indonesia yaitu membedakan antara ciri-ciri desa di Jawa dan yang di luar Jawa.
Oleh karena itu perlu ditegaskan bahwa tajuk diskusi Pertemuan Dua Tradisi tidak hanya bersifat dikotomik antara kampus dan desa semata-mata melainkan “kampus dengan berbagai aliran pemikirannya” dan “desa dengan berbagai jenisnya”.
Sedangkan topik bahasan kali ini tentang “Validitas, Representasi, dan Kuasa dalam Dialog Pengetahuan” adalah mengenai perbandingan posisi masing-masing pihak (kampus dan desa) dalam perbincangan pengetahuan. Jika pendapat ini mengandung kebenaran maka pengertian sehari-hari mengenai kampus adalah identik dengan kota. Letak kampus kebanyakan berada di wilayah perkotaan. Jarang sekali kampus yang berlokasi di pedesaan. Atau, walaupun lokasi kampus berada di pedesaan, pemikiran ataupun perspektif kampus tentang desa selalu bersifat progresif, bahkan boleh dikatakan bahwa kampus selalu memposisikan sebagai super struktur (supraordinat), sedangkan desa diposisikan sebagai objek, sebagai subordinat (infrastruktur) dari pengetahuan.
Kalau diskusi kali ini ingin mencari jawaban bagaimana pola hubungan terbaik dalam dialog antar tradisi kampus dan tradisi desa, paper singkat kali ini menawarkan pandangan singkat dari perspektif kampus.
Hibridasi Ekslusivisme dan Inklusivisme
Kampus, dalam konteks dialog perbandingan ini, identik dengan ilmuwan (teoritisi). Oleh karena itu, sebagai subjek yang “memotret” desa perspektifnya perlu dibedakan dengan perspektif praktisi (perspektif kepala desa, misalnya). Sebagai kumpulan teoritisi, kampus memiliki otoritas penjelajahan yang lebih luas dalam “memotret” desa, juga bentangan waktu yang tidak terbatas. Sedangkan praktisi dibatasi oleh hambatan teknis, peraturan maupun administratif. Oleh karena itu waktunya pun menjadi terbatas, baik oleh ketatnya perencanaan maupun oleh tuntutan prioritas kasus yang lainnya. Dalam pengertian seperti ini, konstelasi hubungan antara kampus dan desa adalah bahwa desa tersubordinasi oleh kampus. Seolah kampus memiliki otoritas yang lebih bebas daripada desa.
Oleh karena itu, dalam beberapa hal kampus memang harus bersifat eksklusif dalam arti kampus harus mempunyai superioritas konsep dengan segenap kelengkapannya bagi desa. Kampus harus mampus memberikan model-model perubahan bagi desa.
Di sisi lain, kampus harus sekaligus menjadikan desa sebagai sumber masalah bagi diri kampus sendiri. Kampus harus bersifat inklusif terhadap desa, kampus harus memiliki legitimasi sebagai bagian penting dari desa. Dalam falsafah pendidikan Indonesia sering kita mengenali Ing ngarso sung tulodho, Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani. Kampus harus menjadi teladan di depan, harus bisa membangun motivasi di tengah masyarakat, dan memberdayakan (mendorong dengan sepenuh kekuatan) masyarakat dari belakang.
Oleh karena itu, dalam rangka keteladanan kampus harus mampu memberi contoh, sehingga pola hubungan dua tradisi itu (seolah) bersifat subordinatif (atas-bawah). Dalam bentuknya yang konvensional, penelitian (proses maupun hasilnya) merupakan fungsi eksklusif kampus dalam membangun dimensi keteladannya.
Sedangkan inklusivitas mencerminkan posisi desa sebagai bagian penting dari apa yang harus dilakukan oleh kampus. Baik di posisi tengah maupun di belakang, desa merupakan sumber gagasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi kampus. Dalam bentuk yang konvensional, pengabdian kepada masyarakat, program KKN mencerminkan inklusivitas kampus. Itulah sebabnya hibridasi (penggabungan) laku eksklusif dan laku inklusif menjadi penting untuk selalu dijadikan landasan tradisi kampus dalam dialog terhadap tradisi desa.
Perubahan Kemana?
Dalam TOR (Term of Reference) diskusi kali ini disinggung bahwa tradisi desa sering (bahkan selalu) termarginalisasi oleh pembangunan yang datangnya dari penguasa yang didukung oleh kampus, yang kalau dipahami secara salah seolah-olah tradisi desa seharusnya dilestarikan atau diabadikan. Apakah betul demikian?
Dalam konteks pembangunan ini, pengertian perubahan menjadi topik sentral bagi pola hubungan yang baik bagi kampus maupun desa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sinkronisasi polah hubungan dua pihak ini:
- Kedua belah pihak harus sepenuhnya menyadari bahwa perubahan (atau pembangunan model apapun) tak mungkn dapat dihindari begitu saja. Artinya, baik kampus maupun desa harus menyediakan ruang untuk berubah, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak lain.
- Kalau tidak berkenan berubah, ya tidak perlu dialog. Jangan ikut dialog kalau tidak ingin berubah.
- Perubahan harus diartikan kearah perbaikan (bukan menjadi perburukan atau pembusukan). Dalam hal ini, perbincangan mengenai baik-buruk harus disadari sebagai forum yang mencerminkan keberadaban kita.
- Melestarikan tradisi desa bukan merupakan hal yang buruk, tetapi tidak semua tradisi harus dan bisa dilestarikan. Tradisi tidak mungkin hidup dari dan oleh dirinya sendiri, melainkan oleh rasionalitas manfaat bagi penggunanya.
- Bagi kampus, inovasi sangat penting, tetapi tidak semua inovasi mengandung kegentingan yang bermanfaat bagi masyarakat. Inovasi masa depan tak akan pernah berguna karena masa depan tidak pernah ada. Pemimpin masa depan selalu tidak kompatibel dengan realita masyarakat masa sekarang. Eksklusivitas kampus tidak harus setinggi langit yang mengawang-awang, melainkan sekedar menara gading yang memberi iming-iming masyarakatnya sekarang juga, bukan besuk.
- Pembangunan desa bukan berarti mengubah desa menjadi kota, melainkan memperbaiki desa supaya memiliki posisi tawar menawar yang selalu lebih baik terhadap pihak lain.
- Pelestarian tradisi desa secara ekstrim, mengakibatkan masyarakatnya menjadi xenophobist (takut terhadap orang lain/asing). Oleh karena itu, desa memang harus siap berubah, ke arah yang lebih baik. Semoga!
Medio Mei 2025
Candi Gebang Permai
Prof. Dr. Tulus Warsito, M.Si.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta