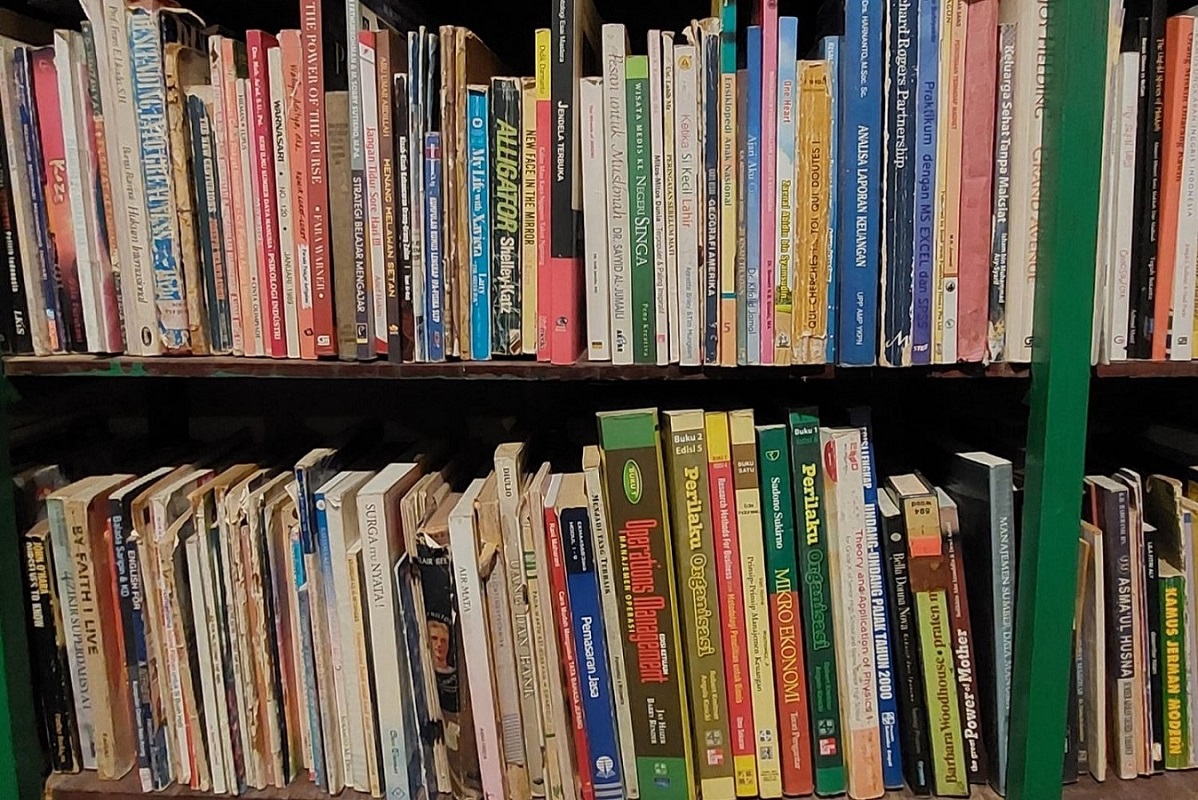Sumber ilustrasi: pixabay
Oleh: Pandu Sagara
24 Mei 2025 12.55 WIB – Umum
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dahulu, narasi bahwa negara agraris demikian kuat. Sejak taman kanak-kank hingga dewasa, dengan berbagai porsinya, narasi negara agraris disajikan, hampir setiap saat. Bahkan tidak jarang dalam sambutan-sambutan acara dalam momen kenegaraan, peringatan hari nasional dan keagamaan, narasi tersebut terselip. Entah disengaja, atau tidak. Namun yang sangat terasa adalah gerak ke arah pembentukan kesadaran tentang kekuatan sektor pertanian. Pencapaian swasembada beras pada medio 80an, sangat mungkin menjadi bagian dari narasi besar tersebut. Di masyarakat sendiri, beras menjadi simbol dari status sosial.
Apakah narasi besar tersebut kongruen dengan pertumbuhan minat untuk bekerja di sektor pertanian? Atau, apakah narasi besar tersebut mendorong peningkatan minat untuk bekerja dan mengandalkan sektor pertanian? Lantas, ketika agenda pembangunan bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri: apakah hal tersebut juga diikuti oleh transformasi angkatan kerja? Apakah telah direncanakan dengan seksama oleh pembangunan, proses transformasinya? Apakah transformasi tersebut berarti migrasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke industri? Atau seperti apa? Pertanyaan-pertanyaan ini memang terasa seperti tidak berujung. Mengapa perlu diajukan? Agar kita semua menyadari keadaan, dan terutama keadaan saat ini. Dan yang penting adalah jelas problem dan jelas pula sikap kita.
Penurunan Regenerasi
Penurunan regenerasi petani adalah kondisi di mana semakin sedikit jumlah generasi muda yang bersedia atau mampu melanjutkan kerja sebagai petani, sehingga terjadi ketimpangan usia dalam populasi petani yang didominasi oleh kelompok usia lanjut. Setiap desa, mestinya dapat menyajikan data riil, berapa anak petani yang menjadi petani, dan berapa anak-anak desa yang tetap bermukim di desa. Meskipun tanpa riset sistematis, telah dapat diketahui, berdasarkan data sekunder, bahwa anak petani pada umumnya tidak menjadi petani. Terutama karena orang tua tani, tidak menginginkan anaknya menjadi petani. Selain itu, anak-anak desa hanya sedikit yang menetap di desa, atau hanya sedikit yang terpelajar bersedia kembali membangun desanya, atau membangun pertaniannya.
Data tersebut menjadi lebih mengejutkan ketika menyingkap proses pembelajaran di pendidikan tinggi pertanian: apakah sarjana pertanian pertama-tama pergi bertani, atau mencoba peruntungannya ke sektor di luar pertanian? Pengelola pendidikan tinggi pertanian mestinya dapat memberikan data yang dibutuhkan, agar tergambar dengan jelas bahwa minat untuk bekerja di sektor pertanian memang benar-benar tidak sedang baik-baik saja. Apa yang kini tersaji sebagai kenyataan adalah bahwa menurunnya minta angkatan muda (sekitar 19–39 tahun) untuk bekerja sektor pertanian. Alasan bisa sangat beragam, mulai dari akses terhadap lahan, modal, teknologi, maupun karena persepsi negatif terhadap profesi petani yang dianggap tidak menguntungkan dan kurang prestisius. Akibatnya, regenerasi tenaga kerja pertanian tidak berjalan secara berkelanjutan, yang dalam jangka panjang hal ini tentu dapat mengancam keberlangsungan produksi pangan nasional dan ketahanan pangan bangsa.
Pokok Soal
Menurunnya regenerasi petani pertama-tama harus dilihat bukanlah persoalan kurangnya motivasi, melainkan problem yang lebih besar. Hendak dikatakan di sini bahwa angkatan muda tidak serta-merta meninggalkan pertanian karena tidak peduli, melainkan karena sistem yang ada tidak memberikan insentif rasional, akses, atau lingkungan yang mendukung bagi mereka untuk terlibat secara produktif dalam sektor ini.
Pertama, sebagian besar lahan pertanian di Indonesia dimiliki secara turun-temurun dan cenderung terfragmentasi karena pembagian warisan. Petani muda yang tidak mewarisi lahan—terutama anak bungsu atau generasi non-petani, tidak memiliki akses untuk memulai usaha tani. Tidak adanya kebijakan redistribusi lahan yang berpihak pada petani pemula menyebabkan ketergantungan pada orang tua, dan menjadikan profesi petani hanya dapat diakses oleh mereka yang lahir dalam keluarga petani dengan aset lahan.
Kedua, sektor pertanian nasional belum memiliki sistem perlindungan harga yang kuat. Fluktuasi harga hasil panen, biaya produksi yang meningkat (termasuk akibat harga BBM dan pupuk), serta ketergantungan pada tengkulak dan jalur distribusi informal menjadikan pendapatan petani tidak stabil. Dalam situasi ini, generasi muda melihat pertanian bukan sebagai investasi jangka panjang yang rasional, tetapi sebagai sektor yang penuh ketidakpastian dan tidak layak secara ekonomi.
Ketiga, meskipun ada perkembangan signifikan dalam pertanian digital dan teknologi cerdas (seperti drone, sensor tanah, aplikasi pasar, dan otomatisasi), adopsinya masih terbatas pada segmen yang memiliki modal besar atau akses edukasi tinggi. Petani muda, terutama dari pedesaan, kesulitan mengakses modal awal, pelatihan teknis, dan infrastruktur pendukung. Minimnya program inkubasi agribisnis untuk pemula menambah kesenjangan antara potensi teknologi dan kapasitas SDM muda untuk menggunakannya.
Keempat, profesi petani masih dipandang sebagai pekerjaan kelas bawah, kotor, melelahkan, dan tidak membanggakan. Sistem pendidikan nasional tidak memberikan ruang yang cukup untuk memperkenalkan pertanian modern, bahkan di wilayah pedesaan. Anak-anak muda diajarkan untuk mengejar pekerjaan di sektor formal perkotaan, sementara pertanian tidak ditampilkan sebagai profesi berbasis inovasi dan teknologi.
Jika keadaan tidak segera ditangani, maka dalam 10–15 tahun ke depan, akan ada potensi munculnya keadaan yang merupakan konsekuensinya: (1) Defisit tenaga kerja pertanian, yang akan menurunkan volume dan produktivitas pertanian domestik; (2) Ketergantungan pada impor pangan, yang mengancam kedaulatan pangan nasional; (3) Alih fungsi lahan pertanian karena tidak adanya pengelola muda, sehingga desa kehilangan fungsi produksinya; (4) Kenaikan harga pangan, akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan produksi dalam negeri; dan (5) Terganggunya pembangunan berkelanjutan, karena pertanian merupakan fondasi bagi sistem sosial-ekonomi desa.
Respon
Apa respon otoritas pertanian terhadap keadaan ini? Sebagaimana yang diketahui public, dan dapat diakses dari berbagai media, telah dikembangkan enam langkah berikut ini:
- Pertama, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan pertanian bagi generasi muda melalui program-program vokasi dan magang.
- Kedua, pemberian insentif finansial dan subsidi untuk menarik minat anak muda ke sektor pertanian.
- Ketiga, pengembangan infrastruktur pertanian modern yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja petani.
- Keempat, memfasilitasi akses terhadap teknologi pertanian terbaru, termasuk penggunaan alat-alat pertanian canggih dan metode pertanian berkelanjutan.
- Kelima, penguatan kelembagaan petani melalui pembentukan koperasi dan kelompok tani yang lebih dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman.
- Keenam, promosi dan kampanye untuk meningkatkan citra positif profesi petani di mata generasi muda.
Apakah enam langkah tersebut telah cukup memadai? Dalam percakapan komunitas, berkembang beberapa pemikiran, yang mungkin saja telah menjadi bagian dari keenam langkah tersebut, namun jika diutarakan barangkali akan berbunyi demikian:
Satu, perlunya dipertimbangkan suatu program distribusi atau konversi lahan tidur, eks HGU, dan tanah desa menjadi aset yang dapat dikelola oleh petani muda melalui skema jangka menengah (misalnya konsesi 10–20 tahun dengan supervisi).
Dua, perlu dipertimbangkan untuk mendirikan inkubator agribisnis desa yang menyediakan pelatihan, akses peralatan modern, mentor kewirausahaan, serta kredit lunak berbasis kelayakan usaha, bukan jaminan fisik.
Tiga, perlu dipikirkan integrasi materi pertanian modern, teknologi pangan, dan agripreneurship dalam kurikulum sekolah sejak SD hingga SMA, serta memperkuat jejaring sekolah pertanian rakyat (SPR) dan agrotourism edukatif. Pada intinya meletakkan pendidikan sebagai bagian dari upaya, tentu dengan tanpa mengecilkan makna pendidikan.
Empat, sebagaimana langkah keenam, perlu lebih digencarkan kampanye, melalui media sosial, dokumenter, dan kisah sukses, profesi petani perlu direpresentasikan ulang sebagai pahlawan pangan masa depan yang tangguh, cerdas, dan inovatif.
Lima, perlu dipikirkan mekanisme yang kongkrit untuk perlindungan harga dan jaminan risiko. Otoritas dalam hal ini perlu memikirkan sistem penyangga harga dan asuransi pertanian berbasis teknologi yang dapat melindungi petani dari fluktuasi pasar dan bencana iklim.
Adapun bagi komunitas desa, perlu pula dipertimbangkan: (1) Mendorong kolaborasi antar generasi dalam pengelolaan lahan secara kolektif. (2) Membentuk koperasi pemuda tani berbasis digital dan gotong royong – termasuk memperkuat literasi keuangan inklusi dan koperasi produksi. (3) Menghapus stigma sosial terhadap pekerjaan tani dengan memperkuat rasa bangga terhadap peran sebagai produsen pangan. (4) Mengoptimalkan dana desa untuk menciptakan pusat pelatihan pertanian lokal berbasis teknologi. (5) memperkuat kolaborasi dengan dunia pendidikan, agar pendidikan pertanian menjadi arus utama.
Akhirnya
Regenerasi petani bukan sekadar soal memperbanyak jumlah tenaga kerja di sektor pertanian, tetapi soal menjaga masa depan kedaulatan pangan dan peradaban desa. Masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan moral atau kampanye motivasional semata. Yang dibutuhkan adalah pembongkaran hambatan struktural yang selama ini menutup pintu bagi generasi muda untuk melihat pertanian sebagai jalan hidup yang bermartabat dan menjanjikan. Dengan kombinasi respon, baik dari otoritas, komunitas desa maupun sektor bisnis, tidak hanya akan menyelamatkan pertaniannya, tetapi juga membangun ulang statusnya sebagai bangsa agraris yang berdaulat atas pangannya sendiri.