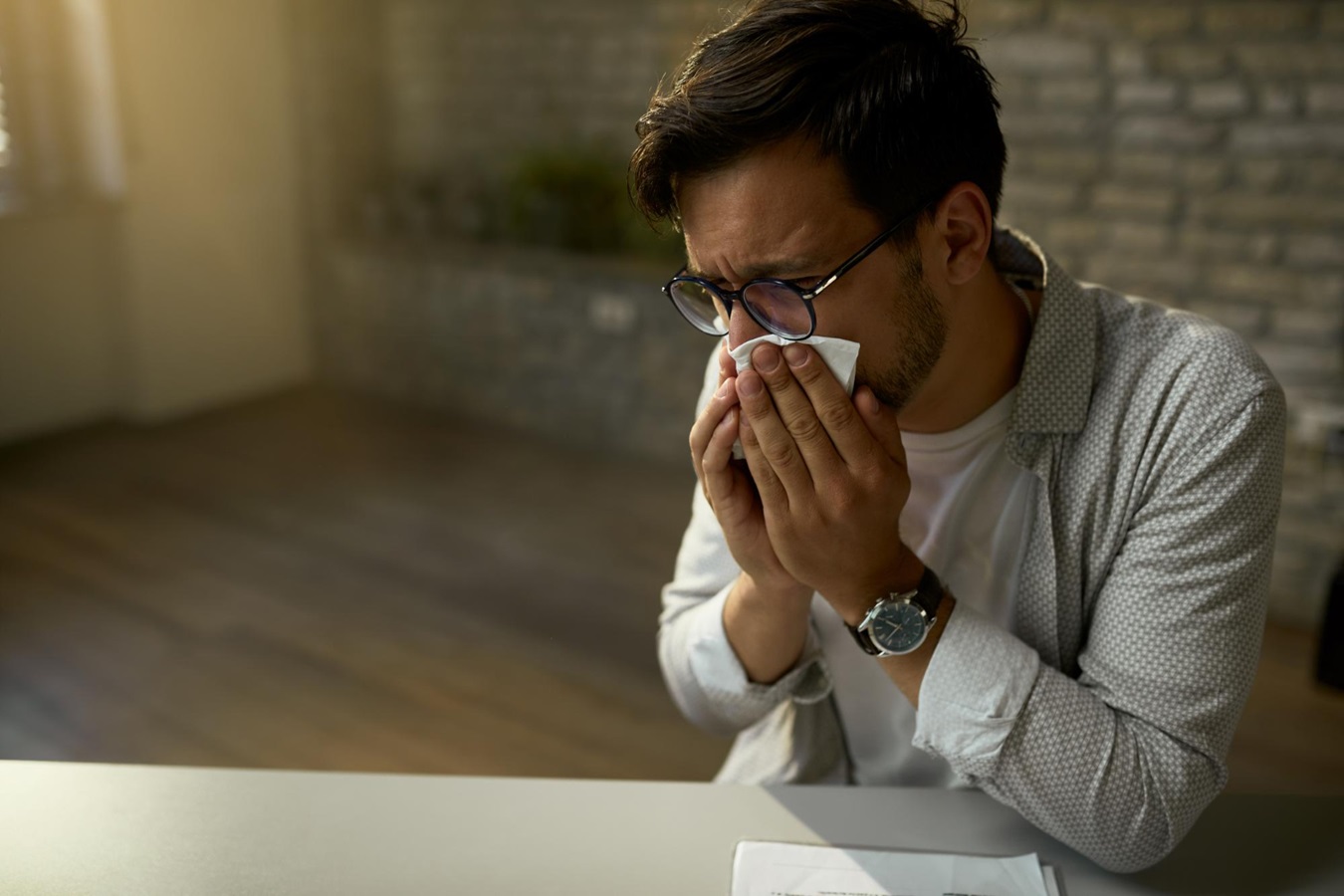Sumber ilustrasi: pixabay
Oleh: Dr. Untoro Hariadi
Dosen Fakultas Pertanian Universitas Janabadra
5 Juni 2025 10.50 WIB – Umum
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Gagasan mengenai penulisan sejarah desa yang diangkat dalam artikel “Sejarah Desa” (desanomia.id, 27/5/25) menawarkan pencerahan penting tentang bagaimana masyarakat desa memahami waktu dan menuturkan masa lalu. Di tengah arus dominan sejarah nasional yang terjebak pada kronologi, data tertulis, dan narasi elitis, tulisan ini menegaskan bahwa desa memiliki cara sendiri untuk mengingat dan mewariskan pengalaman. Sejarah desa, dalam perspektif ini, bukan soal angka dan tanggal, tetapi tentang makna yang hidup dalam tubuh, ritus, lanskap, dan bahasa masyarakat. Sebuah tafsir sejarah yang bersifat kultural dan spiritual, bukan administratif. Penekanan ini penting karena selama ini narasi besar tentang bangsa Indonesia lebih sering disusun dari kacamata pusat kota dan kekuasaan politik, meninggalkan suara desa sebagai sekadar latar belakang.
Namun, upaya menuliskan sejarah desa tidak boleh berhenti sebagai kritik terhadap sejarah mainstream. Ia harus naik satu tingkat menjadi sebuah strategi kebudayaan. Pertanyaannya bukan lagi: apakah sejarah desa mungkin ditulis? Melainkan: bagaimana menjadikannya bagian dari gerakan kesadaran kolektif desa itu sendiri? Dalam konteks ini, penulisan sejarah bukan sekadar kegiatan dokumentasi, tetapi langkah aktif membangun memori sosial yang memperkuat posisi desa dalam menghadapi tekanan modernisasi dan globalisasi. Desa perlu merumuskan ulang dirinya bukan dengan meniru bentuk kota, tetapi dengan menggali kedalaman sejarah dan nilai-nilai yang telah hidup dalam masyarakatnya selama berabad-abad.
Kita perlu menggarisbawahi bahwa sejarah desa bukan hanya “berbeda” dari sejarah negara. Ia menawarkan epistemologi yang berdiri sendiri: sejarah sebagai ingatan yang mengikat komunitas, bukan sebagai verifikasi terhadap masa lalu. Dalam cara pandang ini, waktu tidak bersifat linier tetapi siklik. Peristiwa tidak diingat sebagai data, tetapi sebagai makna yang melekat pada tempat, bahasa, dan laku. Maka, penulisan sejarah desa memerlukan medium dan pendekatan yang mampu menampung kekayaan simbolik ini. Artinya, pengetahuan lokal tidak bisa dipaksa masuk ke dalam format-format penulisan akademik yang rigid. Diperlukan metode yang lentur, yang bisa menjembatani antara cara berpikir masyarakat dengan kebutuhan pencatatan yang bisa diwariskan dan dipelajari.
Langkah pertama yang perlu diambil adalah menjadikan sejarah sebagai bagian dari hidup bersama, bukan hanya milik para peneliti. Sejarah desa harus dikembalikan sebagai milik warga—bukan sekadar objek kajian luar. Ini menuntut proses yang partisipatif, melibatkan warga desa sebagai subjek aktif, bukan informan pasif. Pemetaan cerita rakyat, pendokumentasian nama tempat dan batas wilayah, hingga penelusuran jejak leluhur dalam ritus lokal perlu dilakukan dengan metode yang menghormati bahasa, waktu, dan nilai setempat. Bukan dengan alat ukur dari luar, tetapi dengan empati budaya. Ketika warga dilibatkan sejak awal sebagai pelaku dan pemilik narasi, sejarah menjadi lebih otentik dan bermakna. Mereka tidak hanya menceritakan, tetapi juga memahami bahwa kisah mereka adalah bagian dari fondasi kebudayaan.
Agar pengetahuan ini tidak terputus pada generasi berikutnya, maka dibutuhkan ruang belajar lintas generasi. Tradisi lisan, seperti tembang, cerita rakyat, atau kisah panen pertama, bisa dijadikan kurikulum hidup dalam forum warga, sekolah alam, atau bahkan kelompok belajar anak muda desa. Di sini, sejarah tidak diajarkan seperti mata pelajaran, tetapi dirasakan sebagai bagian dari jatidiri dan orientasi hidup bersama. Proses ini akan menciptakan regenerasi pengetahuan, bukan sekadar konservasi ingatan. Ketika anak muda desa menyadari bahwa cerita kakek-nenek mereka memuat hikmah, strategi bertahan, dan filsafat hidup, maka sejarah menjadi sumber daya moral dan intelektual yang dapat menguatkan masa depan desa.
Selain itu, penting untuk mewaspadai satu jebakan: romantisasi masa lalu. Menulis sejarah desa bukan berarti mengagung-agungkan kehidupan lama secara membabi buta, tetapi justru menggunakannya sebagai cermin untuk memahami tantangan hari ini. Misalnya, bagaimana desa pernah menghadapi krisis air, konflik batas, atau perpindahan penduduk. Di sanalah sejarah menjadi alat refleksi, bukan sekadar nostalgia. Romantisasi masa lalu bisa menutup mata dari kenyataan bahwa sejarah juga berisi konflik, ketimpangan, atau luka yang belum sembuh. Maka, sejarah desa harus dibuka sebagai ruang penyembuhan dan transformasi, bukan sekadar perayaan atas kejayaan yang pernah ada.
Langkah berikutnya adalah membuka kemungkinan ekspresi sejarah dalam bentuk yang beragam. Jangan memaksa sejarah desa untuk berbentuk teks panjang atau laporan ilmiah. Biarkan ia muncul dalam bentuk pertunjukan rakyat, karya visual, film pendek, atau pameran lanskap tempat-tempat bermakna. Biarkan anak muda desa menggunakan teknologi untuk mengarsipkan cerita, membuat peta memori, atau menyusun audio naratif yang menyuarakan pengalaman komunitas. Dengan cara ini, sejarah tidak sekadar ditulis—ia dihidupkan kembali. Medium yang beragam ini juga membuat sejarah menjadi lebih inklusif, menjangkau lebih banyak kalangan, dari anak-anak hingga tetua, dari warga biasa hingga pemangku kebijakan.
Namun semua ini hanya mungkin terjadi jika ada dukungan struktural. Pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan komunitas budaya harus merumuskan strategi bersama agar sejarah desa tidak hanya menjadi proyek dokumentasi, tetapi juga alat perjuangan untuk melindungi ruang hidup, menguatkan identitas, dan memperluas kedaulatan. Dalam konteks itu, sejarah bukan sekadar tentang masa lalu, tetapi tentang masa depan yang ingin diperjuangkan. Dukungan ini bisa berupa regulasi desa yang melindungi situs sejarah, dana khusus untuk riset budaya lokal, atau pelatihan bagi warga dalam mendokumentasikan cerita mereka sendiri.
Penutup
Sejarah desa bukan sekadar tulisan, tetapi napas kolektif yang mengikat komunitas. Ia tidak hidup di dalam buku, tetapi di tubuh, di tanah, dan dalam cerita yang dituturkan dari generasi ke generasi. Menulis sejarah desa berarti menjaga ingatan kolektif agar tidak dilupakan oleh arus modernisasi dan narasi negara yang seragam. Lebih dari itu, menulis sejarah desa adalah cara desa menyatakan dirinya: bahwa ia punya cara sendiri untuk mengenang, memahami, dan melangkah ke masa depan. Sebuah cara yang perlu terus dirawat, diperkuat, dan diwariskan. Karena desa bukan sekadar ruang geografis, melainkan wadah nilai dan identitas yang telah ditempa oleh waktu, kerja, dan kebersamaan.