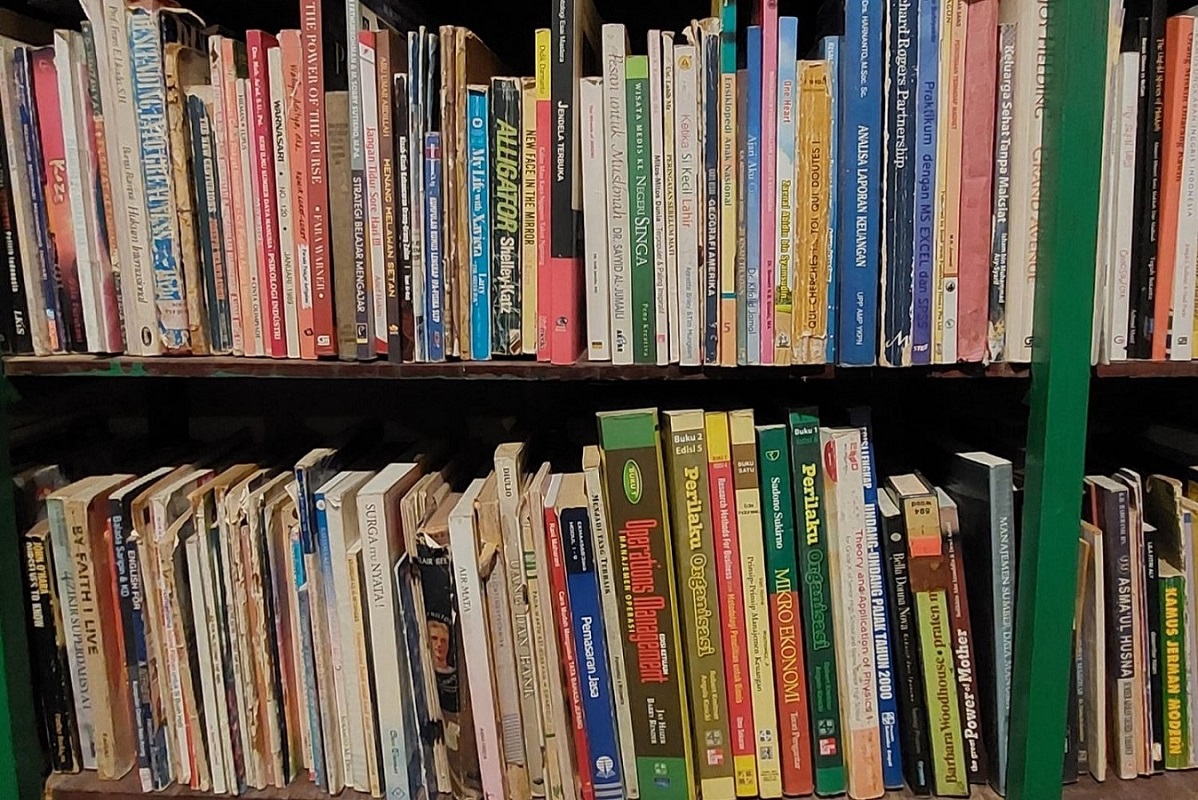sumber ilustrasi: unsplash
Oleh: Untoro Hariadi
16 Apr 2025 14.55 WIB – Umum
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Makna Filosofis
Panen, dalam arti yang paling mendasar, merupakan puncak dari siklus produksi pertanian—momen ketika manusia memanen hasil dari benih yang telah ditanam dan dirawat. Namun, di balik aktivitas fisik ini, tersembunyi lapisan-lapisan makna yang jauh lebih dalam. Secara etimologis, kata “panen” berasal dari bahasa Jawa “panèn” yang berarti mengumpulkan hasil bumi, merefleksikan hubungan primordial antara manusia dan tanah. Dalam tradisi Nusantara, panen tidak hanya bermakna material tetapi juga spiritual—ia adalah titik temu antara kerja keras manusia dan berkah dari yang transenden.
Filosofi panen mencakup setidaknya tiga dimensi penting: siklikalitas, kesalingtergantungan, dan keseimbangan. Siklikalitas mengajarkan bahwa kehidupan bergerak dalam putaran—dari benih menjadi tanaman, kemudian menghasilkan benih baru, lalu kembali ke tanah. Tidak ada yang permanen kecuali perubahan itu sendiri. Kesalingtergantungan mengingatkan bahwa manusia tidak dapat memanen tanpa bantuan berbagai unsur: air, tanah, matahari, mikroorganisme, hingga komunitas yang bekerjasama. Keseimbangan mengajarkan bahwa panen yang berkelanjutan hanya mungkin terjadi ketika manusia mengambil secukupnya, tidak melebih-lebihkan, dan menyisakan untuk regenerasi.
Dalam perspektif kosmologis masyarakat agraris tradisional, panen adalah momen sakral di mana batas antara manusia dan alam, antara yang imanen dan transenden, menjadi tipis. Inilah mengapa ritual-ritual yang mengiringi panen—seperti sedekah bumi, mapag sri, atau slametan—bukan sekadar formalitas kosong, melainkan pengakuan bahwa panen adalah karunia yang melampaui kalkulasi ekonomi semata. Panen adalah bentuk komunikasi antara manusia dengan kekuatan-kekuatan yang lebih besar dari dirinya.
Perspektif Masyarakat Desa
Dalam kehidupan masyarakat desa, panen bukanlah sekadar hasil dari kerja keras di ladang. Ia adalah peristiwa yang sarat makna, merefleksikan kedalaman relasi antara manusia dengan alam, antara individu dengan komunitasnya, dan antara kerja dengan nilai-nilai spiritual. Panen adalah perayaan kehidupan, sekaligus titik temu antara sistem sosial, sistem pengetahuan, dan sistem pangan desa. Dalam konteks ini, panen hadir sebagai penanda kelimpahan yang tidak semata bersifat material, melainkan juga melimpah dalam solidaritas, kearifan, dan keberlanjutan.
Pada tataran sosial, panen menjadi ruang aktualisasi nilai-nilai kebersamaan. Masyarakat desa melibatkan banyak tangan dalam proses panen: saling bantu dalam kegiatan memotong padi, mengangkut hasil, hingga merayakan keberhasilan bersama dalam bentuk kenduri atau selamatan. Tradisi seperti ini memperkuat ikatan sosial dan menegaskan bahwa keberhasilan panen bukanlah milik individu, melainkan milik bersama. Di sinilah terlihat kuatnya semangat gotong royong, di mana kerja pertanian bukanlah kerja individual, tetapi kolektif. Hasil panen bukan hanya untuk dijual, tetapi juga untuk dibagi, untuk disimpan sebagai cadangan, dan untuk menjadi benih musim berikutnya.
Dalam sistem pengetahuan desa, panen adalah buah dari kecerdasan lokal yang telah teruji oleh waktu. Petani tradisional memiliki pengetahuan mendalam tentang ritme musim, arah angin, tanda-tanda binatang, hingga fase-fase bulan. Semua ini bukan sekadar intuisi, melainkan bagian dari sistem pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Ketika panen berhasil, itu bukan hanya hasil dari kerja fisik, tapi juga hasil dari kemampuan membaca alam dengan seksama. Dalam sistem ini, manusia tidak memosisikan diri sebagai penakluk alam, melainkan sebagai bagian dari ekosistem yang saling terhubung. Inilah yang membedakan pengetahuan lokal dari sains modern yang kerap menyingkirkan nilai-nilai spiritual dan kontekstualitas ekologis.
Sementara dalam sistem pangan, panen memiliki fungsi yang sangat fundamental: ia adalah jaminan keberlangsungan hidup. Dalam pandangan masyarakat desa, pangan bukanlah komoditas yang diperdagangkan untuk keuntungan semata. Ia adalah hak hidup. Tanaman pangan, khususnya padi, dihormati bahkan disakralkan. Padi bukan sekadar tumbuhan, tetapi makhluk yang menyimpan kehidupan. Mitos tentang Dewi Sri sebagai penjaga kesuburan mencerminkan bagaimana masyarakat menghormati pangan sebagai bagian dari relasi spiritual. Dengan cara pandang ini, panen adalah wujud dari relasi yang harmonis antara manusia, alam, dan nilai-nilai yang melingkupinya.
Tantangan Hari Ini
Namun, zaman bergerak, dan sistem yang selama ini menopang kehidupan desa menghadapi tekanan hebat. Salah satu tantangan terbesar saat ini adalah pergeseran makna pangan dari hak menjadi komoditas. Dalam arus globalisasi dan logika pasar neoliberal, pangan diperlakukan seperti barang dagangan biasa: diproduksi untuk dijual, bukan untuk memenuhi kebutuhan komunitas. Akibatnya, desa menjadi tergantung pada pasar untuk menentukan harga, pada korporasi untuk benih dan pupuk, dan pada kebijakan eksternal yang kerap mengabaikan kepentingan petani kecil. Proses komodifikasi ini tidak hanya menggerus makna filosofis panen, tetapi juga merusak sistem sosial dan pengetahuan lokal yang telah terbangun selama berabad-abad.
Menurut data FAO (2021), lebih dari 30% lahan pertanian dunia kini digunakan untuk memproduksi komoditas ekspor, bukan pangan lokal. Di Indonesia sendiri, BPS (2023) mencatat bahwa hampir 70% petani kecil tidak lagi menyimpan hasil panennya untuk konsumsi sendiri, tetapi menjual seluruhnya demi kebutuhan ekonomi. Hal ini menciptakan paradoks: petani memproduksi pangan tetapi tidak mampu menjamin ketahanan pangannya sendiri.
Selain itu, krisis ekologis memperparah kerentanan desa. Perubahan iklim menyebabkan musim menjadi tak menentu. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang masif merusak struktur tanah dan mengurangi kesuburan jangka panjang. Krisis air melanda banyak wilayah, sementara akses terhadap sumber daya alam seperti tanah dan air mulai dikuasai oleh segelintir pihak, termasuk korporasi besar dan proyek-proyek industri ekstraktif. Dalam kondisi ini, petani desa tidak hanya kehilangan kendali atas alat produksi mereka, tetapi juga kehilangan ruang untuk menjaga nilai-nilai hidup yang diwariskan.
Lebih jauh, kontradiksi fundamental hadir dalam kebijakan pertanian nasional yang sering kali terjebak dalam dikotomi misleading antara “tradisional” versus “modern”. Modernisasi pertanian yang didorong sejak Revolusi Hijau tahun 1970-an telah meningkatkan produktivitas dalam jangka pendek, namun dengan biaya sosial dan ekologis yang sangat tinggi. Mekanisasi mengurangi kebutuhan tenaga kerja; monokultur menghancurkan keanekaragaman hayati; dan ketergantungan pada input eksternal menggerus kemandirian petani. Yang terjadi bukan hanya hilangnya kearifan lokal, tetapi juga terputusnya transmisi pengetahuan antar generasi, sehingga banyak pemuda desa yang kini tidak lagi mengenal praktik-praktik pertanian berkelanjutan yang telah diwariskan selama berabad-abad.
Merawat Harapan
Meski tantangan besar membayang, sejumlah desa di Indonesia menunjukkan bahwa harapan belum sirna. Mereka merintis jalan untuk membangun kembali sistem pangan lokal yang adil, mandiri, dan berkelanjutan.
Desa Krasak di Boyolali, Jawa Tengah, misalnya, berhasil memenuhi kebutuhan beras warganya secara mandiri meski diterpa dampak El Niño. Pada Oktober 2023, mereka menggelar Festival Pangan Desa sebagai wujud perayaan atas keberhasilan tersebut. Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, menyebut upaya seperti ini penting sebagai fondasi kuat negara dalam menghadapi disrupsi pangan. Dukungan pun datang dari BAPPENAS yang menekankan pentingnya keterlibatan pemuda dan gotong royong dalam mewujudkan transformasi sistem pangan desa (KRKP, 2023).
Sementara itu, Desa Cimerak di Pangandaran, Jawa Barat, memilih jalan diversifikasi pertanian. Dengan memadukan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan kelapa, dan peternakan, mereka mengurangi ketergantungan terhadap satu komoditas dan menjaga keseimbangan ekologi. Penerapan teknologi seperti kolam bioflok untuk budidaya ikan nila menjadi contoh bagaimana inovasi lokal mampu meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan (digitani.ipb.ac.id, 2023).
Cerita inspiratif lainnya datang dari Desa Hewa, Flores Timur. Melalui Sekolah Lapang Biointensive, para petani belajar mengelola lahan secara agroekologis. Hasilnya, panen padi sawah meningkat dan BUMDes dapat mengelola hasil panen sebagai benih dan beras untuk dijual ke desa lain. Model ini menggabungkan pendidikan, kemandirian produksi, dan distribusi komunitas secara cerdas (KRKP, 2020).
Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa desa bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek yang mampu membangun sistemnya sendiri—dengan identitas, nilai, dan strategi yang kontekstual. Mereka menjadi bukti bahwa panen masih bisa menjadi simbol kedaulatan, bukan hanya hasil ekonomi.
Yang perlu kita pahami adalah bahwa gerakan-gerakan lokal ini bukan sekadar upaya romantisasi masa lalu, melainkan sintesis kritis antara kearifan tradisional dan inovasi kontemporer. Mereka menolak dikotomi palsu antara “tradisional” dan “modern”, dan sebaliknya membangun pendekatan yang lebih dialektis: mengambil yang terbaik dari keduanya untuk menciptakan sistem yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan. Dalam paradigma ini, teknologi modern seperti digital farming, pemetaan partisipatif, atau sistem informasi geografis digunakan bukan untuk menggantikan pengetahuan lokal, melainkan untuk memperkuatnya.
Meski demikian, inisiatif-inisiatif lokal ini tidak akan berkembang tanpa perubahan kebijakan struktural. Diperlukan rekonstruksi paradigma pembangunan pertanian yang tidak lagi mengutamakan kepentingan pasar dan korporasi besar, tetapi berpihak pada petani kecil dan ekosistem lokal. Paradigma ini mengakui bahwa pangan bukan semata komoditas, tetapi hak asasi; bahwa keragaman benih dan praktik pertanian adalah kekayaan yang harus dilindungi; dan bahwa petani bukan objek tetapi subjek pembangunan.
Penutup
Panen adalah momen puncak dari kerja, harap, dan doa. Ia menjadi simbol dari relasi yang harmonis antara manusia, alam, dan komunitas. Di tengah gempuran ideologi pasar dan krisis ekologi, panen dapat menjadi titik balik, tempat kita meneguhkan kembali nilai-nilai dasar yang selama ini menopang kehidupan desa. Dengan merawat filosofi panen, kita tidak hanya menyelamatkan sistem pangan desa, tetapi juga merawat kehidupan itu sendiri — kehidupan yang cukup, adil, dan bermartabat.
Dalam konteks Indonesia yang terus bergulat dengan isu ketahanan pangan, pemulihan makna panen menjadi lebih dari sekadar nostalgia kultural. Ia adalah fondasi bagi pembangunan sistem pangan yang berdaulat—sistem yang memungkinkan masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang mereka tanam, bagaimana mereka menanamnya, dan bagaimana hasilnya didistribusikan. Kedaulatan pangan ini tidak hanya menjamin ketersediaan pangan, tetapi juga menjaga martabat petani dan kelestarian lingkungan.
Jalan menuju pemulihan sistem pangan desa mungkin tidak mudah, tetapi bukanlah tidak mungkin. Seperti benih yang ditanam dengan hati-hati, dijaga dengan penuh kesabaran, dan akhirnya menghasilkan panen yang melimpah, upaya kita hari ini adalah investasi bagi masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Panen, pada akhirnya, adalah metafora kehidupan itu sendiri: kita menuai apa yang kita tanam, dan kita menanam untuk generasi yang akan datang.
Dr. Untoro Hariadi
Dosen Fakultas Pertanian Universitas Janabadra