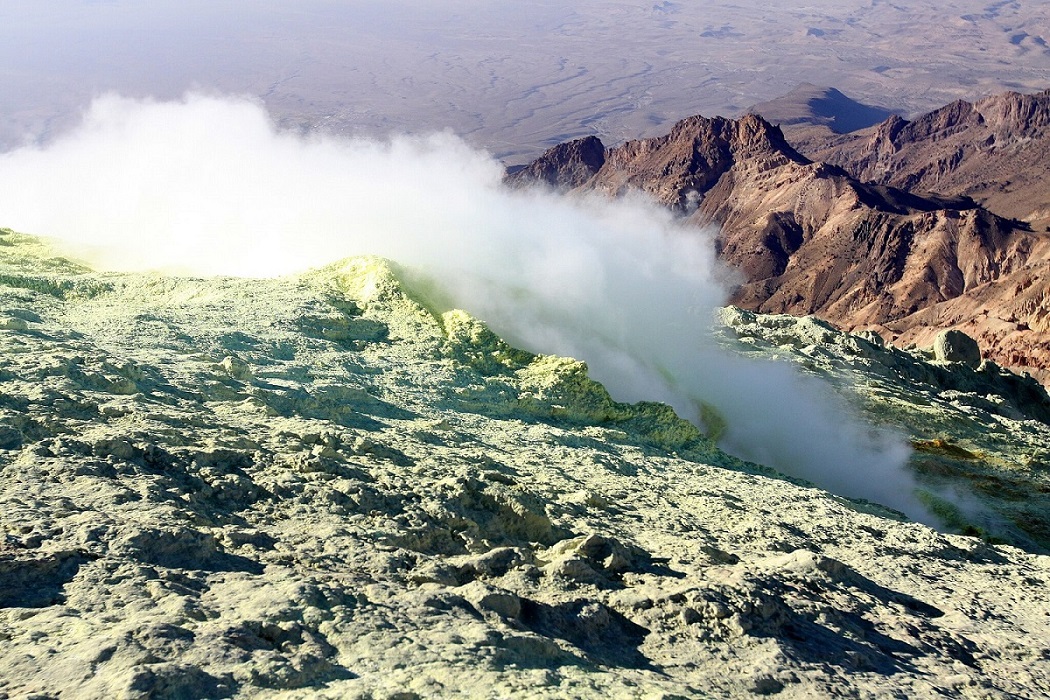Sumber ilustrasi: freepik
Oleh: Dr. Untoro Hariadi
Dosen Fakultas Pertanian Universitas Janabadra
11 Juni 2025 13.40 WIB – Umum
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Di tengah gelombang digitalisasi global, Artificial Intelligence (AI) mulai memasuki ranah yang selama ini dianggap tradisional: pertanian desa. Janji yang dibawa AI adalah efisiensi, prediksi akurat, dan peningkatan hasil produksi. Namun, ketika teknologi ini masuk ke ruang-ruang desa yang memiliki dinamika sosial, budaya, dan pengetahuan lokal yang kompleks, kita harus bertanya: apakah AI benar-benar mampu mendorong kedaulatan pangan desa? Atau justru menciptakan ketergantungan baru yang melemahkan posisi petani dan komunitasnya?
AI dalam sektor pertanian umumnya diaplikasikan melalui drone pemantau lahan, sistem prediksi cuaca, sensor tanah, hingga algoritma yang memetakan pola tanam terbaik berdasarkan data besar (big data). Di permukaan, semua ini tampak menjanjikan. Dalam laporan FAO (2021), disebutkan bahwa “AI dapat membantu petani membuat keputusan lebih baik dengan mengurangi ketidakpastian dalam iklim dan pasar yang berubah-ubah.” Namun, pertanyaannya adalah: siapa yang memiliki, mengakses, dan memahami teknologi tersebut?
Desa bukan hanya tempat bertanam, melainkan ruang hidup yang dilingkupi nilai, tradisi, dan pengetahuan kolektif yang telah diwariskan secara turun temurun. Sistem pertanian desa tidak hanya bicara hasil, tetapi juga relasi antara manusia, tanah, musim, dan komunitas. Ketika AI masuk dengan logika optimasi dan efisiensi, ia bisa saja menyingkirkan intuisi dan kearifan lokal yang tak terkomputasi.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah soal data. AI bekerja berdasarkan data. Maka, lahan, iklim, pola tanam, hingga aktivitas petani direkam, dikumpulkan, dan diolah oleh sistem yang sering kali dimiliki oleh korporasi besar. Di sinilah letak persoalan struktural. Seperti ditulis oleh Shoshana Zuboff dalam The Age of Surveillance Capitalism (2019), “Apa yang dulu menjadi pengalaman manusia kini menjadi data untuk kepentingan ekonomi pihak lain.” Dalam konteks desa, ini berarti aktivitas pertanian warga bisa diekstraksi untuk keuntungan pihak luar, sementara petani sendiri tidak memiliki kuasa atas data yang dihasilkan dari tanah mereka.
AI yang tidak dibangun dalam kerangka keadilan pengetahuan justru bisa melanggengkan relasi timpang antara desa dan pusat-pusat kekuasaan digital. Ketika data pertanian desa menjadi bahan baku model prediktif yang dijual kembali kepada petani, terjadi bentuk baru dari penjajahan digital: desa menjadi penyedia data mentah, namun tidak mendapat kembali nilai tambah dari proses digitalisasi itu. Proses ini mengulangi logika ekstraktif yang selama ini menguras sumber daya alam desa — kini dalam bentuk data.
Kritik ini bukan berarti menolak teknologi. Sebaliknya, kita justru harus memperjuangkan model penggunaan AI yang mendukung kedaulatan desa, bukan menggantikan logika dan nilai yang hidup di dalamnya. Kedaulatan pangan desa bukan hanya soal ketersediaan hasil panen, tetapi juga soal kontrol atas proses produksi, distribusi, dan pengetahuan yang menyertainya. Dalam konteks inilah AI seharusnya diletakkan sebagai alat bantu, bukan sebagai penentu utama.
Pemuda desa memainkan peran kunci dalam jembatan antara dunia teknologi dan komunitas. Mereka lebih adaptif terhadap inovasi digital, tetapi juga masih memiliki keterikatan dengan nilai-nilai komunitas. Di sinilah pentingnya pendidikan kritis tentang teknologi di ruang-ruang desa. Bukan hanya pelatihan teknis tentang cara menggunakan AI, tetapi juga diskusi tentang etika data, kedaulatan digital, dan bagaimana teknologi bisa dipakai tanpa mengorbankan jati diri komunitas.
Ada banyak contoh baik di mana AI dipakai dengan pendekatan komunitas. Di India, proyek Digital Green memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat pertukaran pengetahuan antar petani melalui video lokal. Teknologi digunakan sebagai penguat sistem sosial yang sudah ada, bukan sebagai pengganti. Seperti dinyatakan oleh salah satu pendirinya, Rikin Gandhi, “Teknologi yang baik adalah teknologi yang memperkuat yang sudah ada, bukan yang menggantikannya.” (Gandhi, 2014, TED Talk).
Model seperti ini bisa dikembangkan lebih jauh: misalnya sistem prediksi cuaca lokal yang dibangun dari data komunitas sendiri, sensor tanah yang dikembangkan oleh koperasi petani, atau sistem distribusi pangan desa yang memakai algoritma buatan lokal. Semua ini dimungkinkan jika desa didukung untuk membangun kapasitas teknologinya secara mandiri.
Sayangnya, kebijakan nasional masih banyak menempatkan desa sebagai objek pembangunan digital. Alih-alih mendorong penguasaan teknologi oleh komunitas, banyak inisiatif justru menjadikan desa sebagai pasar pengguna. “Teknologi diciptakan bukan untuk memenuhi kebutuhan petani, tetapi untuk menjadikan mereka sebagai konsumen produk digital,” tulis Jaron Lanier dalam Ten Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now (2018). Perspektif ini harus dibalik. Desa harus dilibatkan sebagai subjek sejak proses desain teknologi, bukan hanya di tahap penggunaan.
Selain itu, penting untuk membangun kesadaran kolektif di desa tentang nilai data pertanian. Data bukan sekadar angka, melainkan bentuk baru dari sumber daya ekonomi dan politik. Seperti ditegaskan oleh Kate Crawford dalam Atlas of AI (2021): “AI bukan kecerdasan netral — ia dibentuk oleh siapa yang membuatnya, dengan data siapa, dan untuk kepentingan siapa.” Maka, komunitas desa berhak menuntut kejelasan atas bagaimana data pertanian mereka digunakan, disimpan, dan siapa yang mengambil manfaat darinya.
Pengetahuan lokal dan AI tidak harus dipertentangkan. Justru saat keduanya dipadukan secara adil dan reflektif, kita bisa membayangkan bentuk baru dari kedaulatan pangan desa yang berbasis pada kolaborasi antar generasi, antara kearifan dan inovasi. AI tidak boleh menghapus intuisi petani, tetapi sebaliknya harus bisa belajar dari pengalaman mereka yang telah berpuluh tahun berinteraksi dengan tanah, iklim, dan benih.
Penutup
AI dalam pertanian desa adalah pisau bermata dua: bisa memperkuat, tetapi juga bisa melemahkan kedaulatan pangan jika tidak dikritisi dan dipandu dengan prinsip keadilan. Untuk itu, kita membutuhkan kombinasi antara inovasi teknologi dan kesadaran kolektif komunitas. Anak muda desa memiliki posisi strategis untuk memimpin proses ini, bukan hanya sebagai pengguna AI, tetapi sebagai pencipta, penjaga nilai, dan penggerak transformasi yang berpihak pada kehidupan desa. AI tidak boleh menjadi pengganti, tetapi pelayan dari sistem pangan desa yang berdaulat, adil, dan lestari.