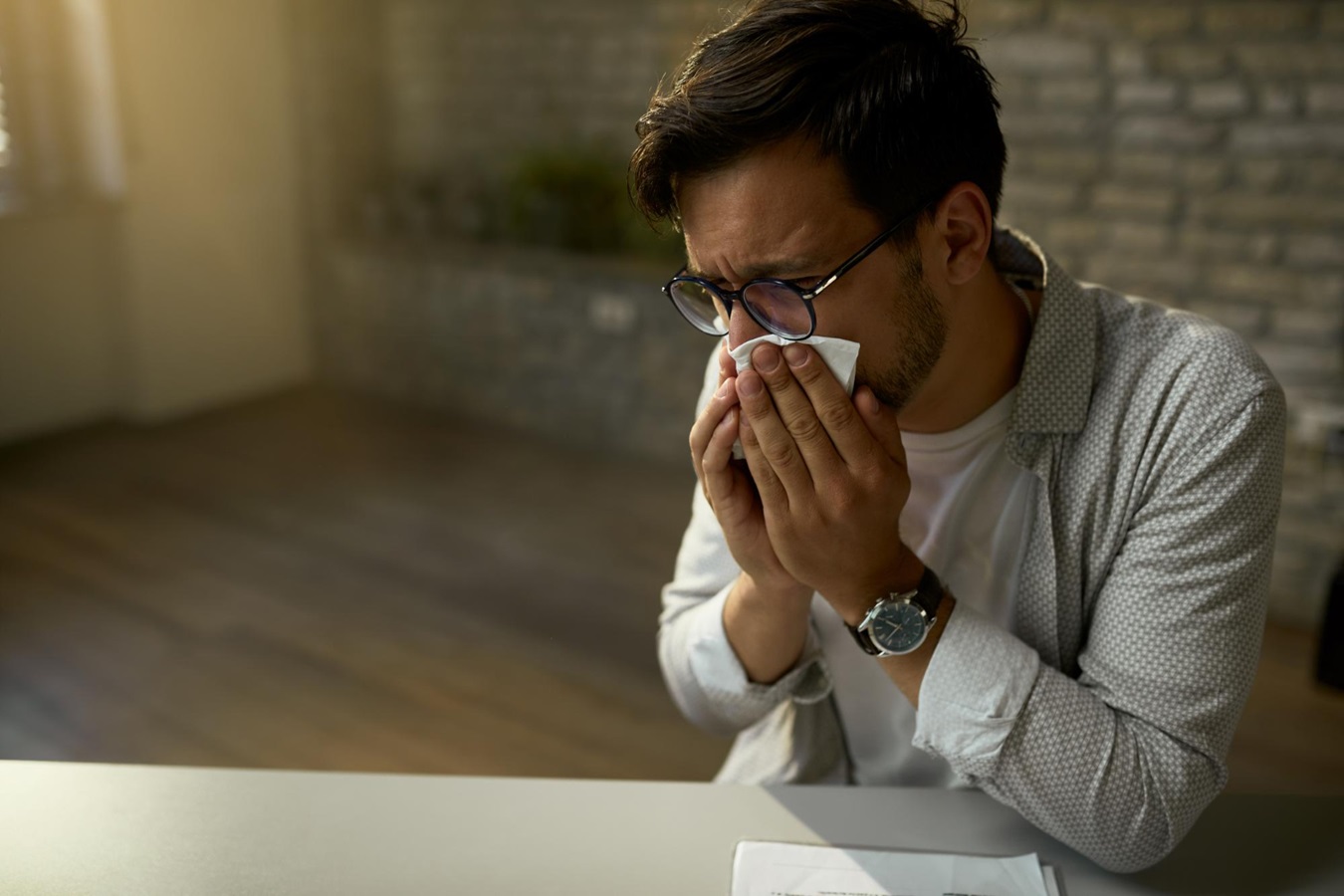Sumber ilustrasi: unsplash
Oleh: Untoro Hariadi
18 Mei 2025 17.45 WIB – Umum
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Di banyak penjuru negeri, wajah desa kini semakin sulit dibedakan dari kota. Jalanan dibeton, ruko-ruko berdiri di sisi kanan-kiri, warung kopi modern menggantikan pos ronda, dan lahan pertanian disulap menjadi klaster perumahan. Semua tampak serba maju, serba cepat. Namun di balik modernisasi itu, muncul kegelisahan yang dalam: desa perlahan kehilangan jati dirinya.
Pembangunan yang menjadikan desa sebagai bayang-bayang kota bukanlah fenomena baru. Ia tumbuh dari paradigma pembangunan sentris-kota, yang menempatkan kota sebagai tolak ukur kemajuan dan desa sebagai ruang tertinggal yang harus segera “diperbaiki”. Dalam logika ini, desa dianggap belum jadi, belum modern, belum berkembang. Padahal, sebagaimana dikatakan oleh Ivan Illich (1971), “Ketika pembangunan dilakukan tanpa menghormati struktur lokal, yang terjadi bukanlah kemajuan, tapi pemusnahan halus.”.
Pandangan yang menempatkan kota sebagai parameter kemajuan ini kemudian melahirkan proyek-proyek pembangunan desa yang seragam dan tidak kontekstual. Program Dana Desa, meski membawa manfaat besar, sering diarahkan untuk membangun infrastruktur fisik yang meniru kota. Pembangunan jalan beton, gapura monumental, hingga kampung wisata dengan estetika artifisial menjadi indikator kesuksesan. Sementara itu, pertanian yang menjadi nadi desa justru kerap terpinggirkan.
Ketika desa dinilai dengan kaca mata kota, maka yang dianggap berhasil adalah desa yang “seperti kota”. Desa yang ramai, penuh bangunan, dan bergaya urban. Namun, benarkah itu ukuran kemajuan? Atau kita sedang menyiapkan kubur bagi pengetahuan lokal, solidaritas sosial, dan keberlanjutan ekologis yang selama ini hidup di desa?
James C. Scott (1998) mengkritik cara negara modern melihat masyarakat sebagai peta-peta yang harus disederhanakan. Ia menyebut bahwa negara cenderung menciptakan “legibility” atau keterbacaan, dengan mereduksi keragaman lokal menjadi sistem yang rapi dan seragam. Dalam konteks desa, pembangunan yang “rapi” dan “terukur” seringkali mengorbankan praktik hidup lokal yang kompleks, tidak terstandar, tapi justru berdaya guna.
Apa yang terlihat tidak teratur oleh negara––seperti sistem irigasi tradisional, pola tanam campuran, atau pembagian kerja berbasis keluarga––sebenarnya adalah bentuk keteraturan sosial yang kaya. Namun semua itu seringkali diabaikan dalam logika pembangunan yang ingin cepat, terukur, dan seragam.
Pengabaian terhadap kearifan lokal ini semakin terasa dampaknya ketika kita melihat bagaimana dalam banyak kasus, pembangunan desa justru membuka pintu bagi masuknya kapital besar yang merombak tata ruang desa. Proyek food estate, kawasan industri, hingga jalan tol membelah desa-desa dengan dalih investasi dan konektivitas. Tanah-tanah pertanian dikavling untuk perumahan elit, dan masyarakat lokal yang tak sanggup mengikuti laju ekonomi baru tersingkir secara perlahan.
David Harvey (2006) menyebut ini sebagai “accumulation by dispossession”, yaitu proses pengambilalihan ruang hidup rakyat demi akumulasi modal. Desa tidak hanya kehilangan tanah, tapi juga kehilangan kedaulatan.
Perampasan ruang hidup ini membawa dampak yang lebih mendalam, karena lebih dari sekadar bangunan, desa menyimpan nilai-nilai yang tidak dapat dibeli: gotong royong, tepo seliro, sistem pertanian lokal, dan cara hidup yang cukup. Namun kini, nilai-nilai itu mulai ditinggalkan. Remaja desa lebih bangga bekerja sebagai kurir di kota daripada bertani di sawah. Pertanian dianggap kuno, kotor, dan tidak menjanjikan. Konsumsi meningkat, solidaritas melemah.
Jika pembangunan terus berorientasi kota, desa akan kehilangan keunikan dan menjadi bayang-bayang semu. Seperti kata Amartya Sen (1999), “Pembangunan harus membebaskan, bukan menyeragamkan. Yang penting bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, tapi kemampuan manusia untuk menjalani hidup yang ia nilai bermakna.”.
Mencermati kondisi yang semakin mengkhawatirkan ini, perlu disadari bahwa kritik ini bukan berarti menolak pembangunan, tapi menolak arah pembangunan yang menghapus akar. Kita perlu membayangkan ulang desa sebagai ruang hidup yang otonom, yang membangun berdasarkan kekuatan dan kebutuhan sendiri, bukan berdasarkan cetak biru dari pusat.
Beberapa desa telah menunjukkan jalan ini. Di Kulon Progo, misalnya, gerakan pertanian organik dan koperasi pangan membuktikan bahwa desa bisa sejahtera tanpa harus menyerupai kota. Di Lombok Utara, komunitas adat membangun tata kelola air secara mandiri melalui pranata lokal. Di Bali, konsep “Tri Hita Karana” menjadi dasar pembangunan yang seimbang antara manusia, alam, dan spiritualitas.
Model-model ini menunjukkan bahwa desa bisa maju tanpa kehilangan jiwa. Desa tidak harus menjadi kota untuk berkembang. Desa cukup pangan, cukup air, cukup solidaritas adalah bentuk kemajuan yang tak bisa diukur dengan indikator kota.
Melihat berbagai contoh keberhasilan tersebut, kini saatnya kita bertanya ulang: untuk siapa pembangunan desa diarahkan? Apakah untuk kesejahteraan warga desa, atau untuk kepentingan pasar dan elite? Apakah pembangunan membuat desa makin hidup, atau justru makin rapuh?
Penutup
Menjadikan desa sebagai kota adalah bentuk kegagalan imajinasi pembangunan. Kita butuh cara baru yang berangkat dari akar––dari tanah yang diinjak, dari air yang diminum, dari solidaritas yang diwariskan. Karena desa bukan ruang kosong yang harus diisi, tetapi ruang hidup yang harus dihormati.
Dr. Untoro Hariadi
Dosen Fakultas Pertanian Universitas Janabadra