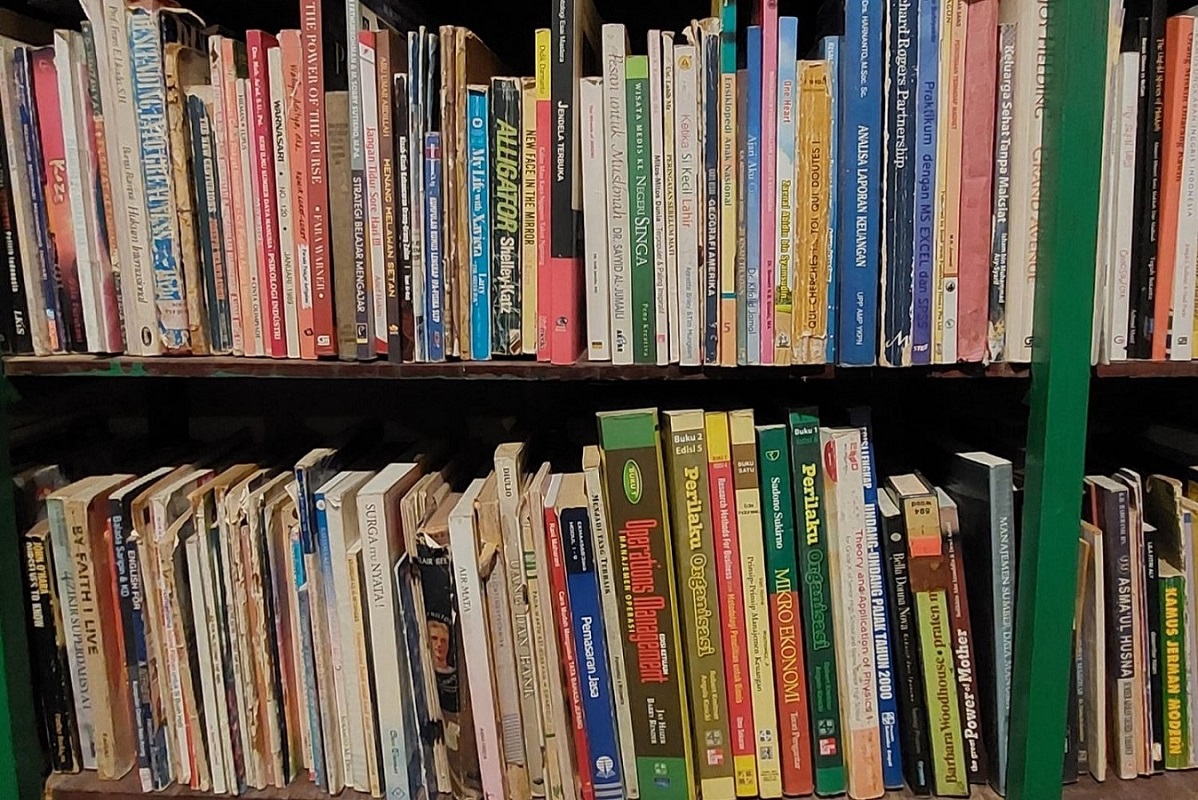Sumber ilustrasi: Dokumentasi Pribadi
Oleh: Pinurba Parama Pratiyudha, S.Sos., M.A.
Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fisipol, Universitas Gadjah Mada
30 Oktober 2025 09.35 WIB – Umum
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pada mulanya penulis tidak ada niat untuk membuat terusan dari tulisan ‘Produksi Pengetahuan dan Reproduksi Sosial’. Akan tetapi ada seorang rekan merespons tulisan tersebut dengan dua pertanyaan: (1) Apa yang sebenarnya dimaksud sebagai produksi pengetahuan dan reproduksi sosial?; (2) Lantas bagaimana jembatan antara kedua hal tersebut dapat dibangun secara konkret, langkah-langkah strategis apa yang bisa kita lakukan atau setidaknya gagas? Memang sejatinya tulisan tersebut ditulis dalam keresahan yang tidak terstruktur sehingga menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hal yang diwajarkan sekaligus pula menjadi proses yang menarik dalam bagian diskusi gagasan dan argumen secara dinamis.
Penulis pada tulisan ini akan memulai dari pertanyaan pertama, apa itu produksi pengetahuan dan reproduksi sosial itu sendiri. Produksi pengetahuan merupakan proses yang aslinya melekat pada manusia, sebagai makhluk yang diberi anugerah akal budi sebagai sarana manusia untuk menginterpretasikan dan mengabstraksikan suatu fenomena yang muncul di sekitarnya. Alih-alih menjadi proses yang selalu dikonstruksikan sebagai milik seorang akademisi, produksi pengetahuan sejatinya adalah proses yang dimiliki setiap manusia secara naluriah. Ketika manusia secara nyata mengalami – dalam aktivitas spesifik yaitu melihat – fenomena kematian, manusia akan kemudian secara naluriah memproses apa yang ia lihat dan rasakan dari fenomena tersebut dalam alam berpikirnya. Dari proses itulah muncul suatu abstraksi akan bentuk-bentuk kematian itu seperti apa. Abstraksi ini kemudian akan berkembang menjadi lebih kompleks ketika manusia membangun keterkaitan dengan pengalaman lain, sebagai contoh adalah pengalaman lapar. Kelaparan ternyata dapat berujung pada kematian oleh karena manusia akan mengalami kondisi fisik yang lemah dan buruk sehingga berujung pada kematian ketika terus berkepanjangan. Inilah proses produksi pengetahuan secara sederhana.
Sementara itu, reproduksi sosial dapat dimaknai sebagai proses manusia mempertahankan kebutuhan hidupnya baik dari segi ekonomi, sosial, dan ekologi. Ketika manusia mampu membangun abstraksi soal lapar dan kematian, di situlah kemudian dirinya akan mulai berpikir bahwa perlu adanya suatu aktivitas bertahan hidup. Lahirlah kemudian aktivitas mencari makan untuk menjaga keberadaan dirinya sendiri. Lambat laun dalam pencarian makan inilah manusia menyadari bagaimana eksistensi lingkungan alamnya, keberadaan sesamanya makhluk manusia, dan ancaman-ancaman kematian lainnya sebagai suatu pengetahuan. Pemahaman tersebut kemudian melahirkan reproduksi sosial yang semakin kompleks seperti berkeluarga, bercocok tanam, hingga berkomunal dalam suatu struktur yang disepakati.
Berangkat dari analogi di atas dapat dipahami juga bagaimana produksi pengetahuan dan reproduksi sosial sebagai proses yang saling berkaitan satu dengan lain. Produksi pengetahuan atas lapar melahirkan reproduksi sosial usaha mencari makan; usaha mencari makan pun berujung menjadi produksi pengetahuan soal kematian ketika reproduksi sosial tersebut tidak membuahkan hasil. Kesadaran primitif ini – kalau meminjam istilah Marxisme – sejatinya tidaklah berubah pada masyarakat modern saat ini. Pemikiran Marxisme mungkin berpendapat bahwa kehadiran kapital menciptakan pengalihan proses ekonomi primitif menjadi ekonomi modern, namun pada hakikatnya keberadaan kapital hanya menjadi suatu abstraksi yang menggantikan nilai fungsi dari suatu benda atau aktivitas semata. Peradaban manusia menemukan mesin uap sejatinya berangkat dari proses pengamatannya atas gerak uap air dan bagaimana uap air menggerakkan suatu massa padat. Suatu pengamatan akan alam dan fenomena gaya gerak ini membawa lahirnya reproduksi sosial berupa industrialisasi dan relasi kerja industri di dalamnya (dan dalam proses reproduksi sosial tersebut juga hadir proses produksi pengetahuan yang lebih spesifik lagi). Sehingga secara naluriah kedua proses yang diistilahkan sebagai primitif tersebut masih terjadi hingga manusia modern.
Namun tidak bisa dihindari pula, apa yang dibawa pemikiran Marxisme sebagai kapital memberikan suatu efek fatamorgana atas aktivitas produksi pengetahuan dan reproduksi pengetahuan yang naluriah terjadi. Sudah tentu kapital adalah produk dari produksi pengetahuan dan eksistensinya tidak hanya menjadi pengganti nilai fungsi, namun juga menjadi salah satu abstraksi atas jembatan antara produksi pengetahuan dan reproduksi sosial. Pengetahuan yang hakikatnya sebagai produk yang terbuka kemudian menjadi suatu produk yang tertutup ketika pengetahuan itu dikomodifikasikan sebagai suatu kapital melalui pemberian akses secara terbatas atas pengetahuan terhadap usaha penciptaan reproduksi sosial yang baru. Pada proses inilah kemudian lahir industri pendidikan dan pengetahuan, yang pada akhirnya membuat proses produksi pengetahuan menjadi suatu proses reproduksi sosial.
Historisasi tersebut membawa pada kekacauan alam berpikir manusia dalam melakukan produksi pengetahuan. Lahirlah kemudian produksi pengetahuan yang memunculkan reproduksi sosial menindas dalam ruang kolonialisme. Pengetahuan yang muncul pada satu ruang dan waktu penguasa dibawa kepada ruang dan waktu yang dikuasai dan melahirkan produksi pengetahuan yang ahistoris pada konteks yang dikuasai. Akhirnya terbangun suatu fatamorgana pengetahuan dan realitas sosial yang sejatinya terlepas dari ruang hidup tempat manusia bermukim. Sejatinya naluriah untuk berproduksi pengetahuan dan bereproduksi sosial yang dilakukan tertutup oleh suatu ilusi-ilusi abstrak yang jauh dari realitas bermukim seorang manusia.
Keterjebakan inilah yang membawa pada pergulatan eksistensi akademik menjadi pekerjaan rumah yang berkepanjangan. Dunia akademik memiliki fungsi industri sebagai pelaku utama produksi pengetahuan, namun pada hakikatnya pelaku akademik jugalah manusia yang melekat dengan realitas reproduksi sosial secara berkelanjutan. Pergulatan ini semakin menyentuh secara eksistensial ketika produksi pengetahuan yang dilakukan para pelaku akademik dialienasikan dengan reproduksi sosial yang dilakukannya.
Abstraksi paradoks yang dimunculkan dalam tulisan ini sejatinya tidak untuk membawa pembaca untuk berpikir kembali pada proses berkehidupan yang primitif kembali. Penulis pun tidak ingin membawa kompleksitas tersebut untuk didekonstruksikan ulang, oleh karena sudah banyak para pemikir yang membahas dan melakukan dekonstruksi tersebut. Perihal berikutnya yang akan penulis bawa adalah suatu gagasan transkonstruksi dalam dunia akademik dan pendidikan kita. Inilah yang kemudian pada tulisan berikutnya akan bersinggungan dengan pertanyaan kedua sekaligus dalam modifikasi yang lebih spesifik: bagaimana kemudian kita perlu melakukan transkonstruksi proses dua arah dari produksi pengetahuan dan reproduksi sosial? Serta kemudian juga bagaimana dunia akademik dan pendidikan merespons realitas tersebut?